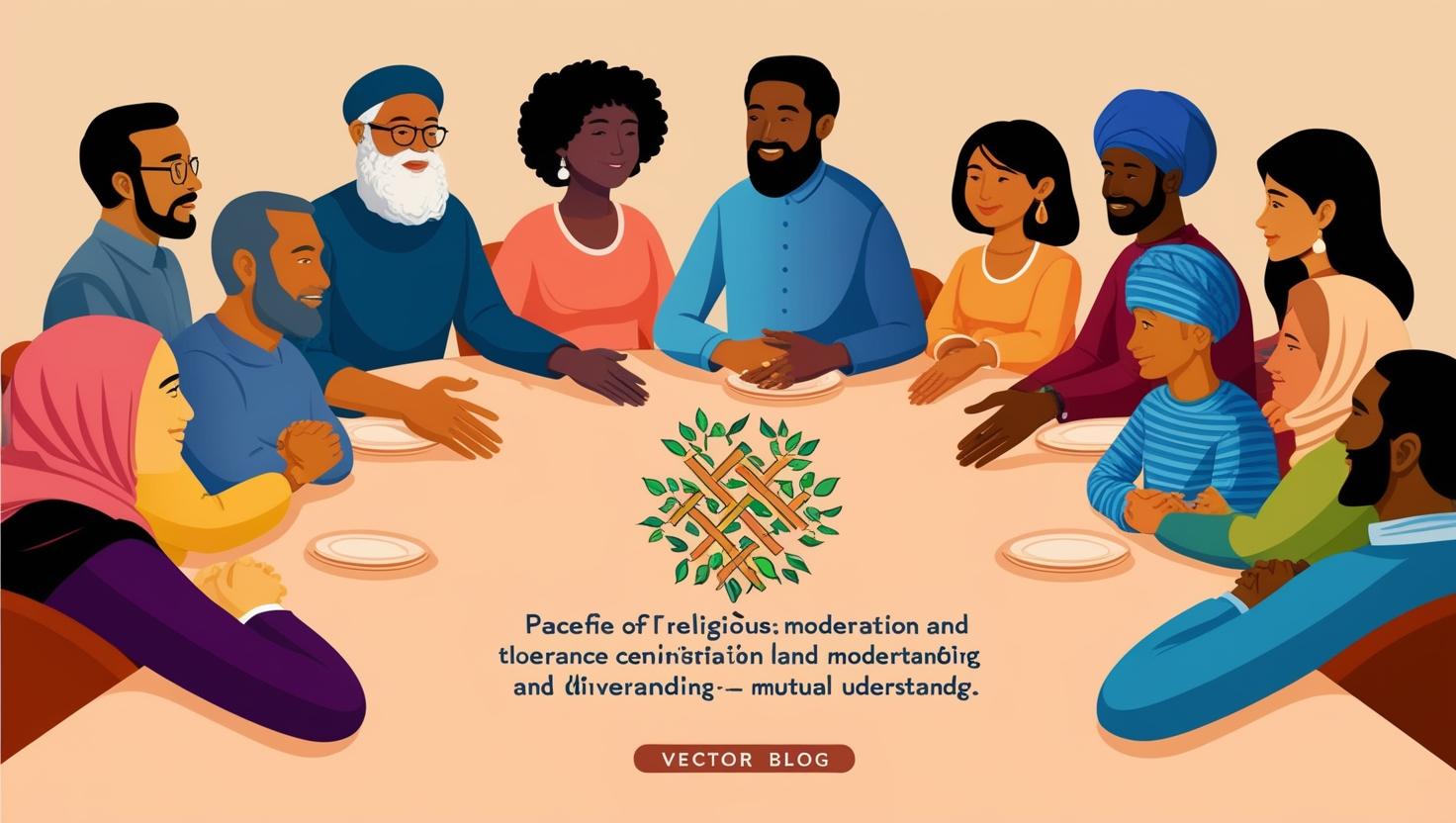Belajar Sosiologi– Beberapa waktu yang lalu, saya membaca tulisan dari salah satu mahasiswa UGM di mojok dengan narasi “4 Tahun Kuliah di UGM, Saya Baru Menyesal Sudah Mengambil Jurusan Sosiologi yang Ternyata Susah Dapat Kerja dan Gaji Ngga Sesuai Harapan” begitulah kira-kiranya. Perasaan saya cukup dibuat mak deg dan ya cukup senyum-senyum mendengar bacaan yang menarik ini. Saya memahami di tengah kondisi yang saat ini, apa yang diharapkan dari seseorang lulusan sosiologi. Namun, biar supaya jelas saya rasa ada yang perlu diluruskan, bukan pembelaan tetapi menolak cara berpikir yang terlalu simplistis dalam menilai sebuah bidang keilmuan.
Kilas balik, dulu kalau ada yang nanya “Ngapaian sih belajar sosiologi, Kan cuman ngomongin masyarakat doang” atau “Nanti lulus kerjanya jadi apa?” dll. Waktu itu sih paling cuman senyum-senyum sambil mikir, Ya begitulah. Jujurly saya bukan orang yang dari awal ngebet sama jurusan ini, pasti dong awalnya punya mimpi masuk jurusan TOP rumpun soshum kaya ekonomi, psikologi, atau hukum. Tapi siapa sangka, karena sosiologi, justru saya menemukan cara pandang dan yang bikin saya memahami dunia, diri saya sendiri dan semesta dengan lebih baik.
Per hari ini saya masih freshgaduate, saya lulus dengan semangat setengah-setengah. Harapan pastinya pengen dong dapat segera kerja dan dapat gaji yang cukup. Tapi tidak semudah itu ferguso, Loker loker yang sesuai dengan jurusan sosiologi sepertinya tidak banyak orang yang membutuhkannya.
Yang ada cuma tawaran jadi peneliti lapangan dengan gaji pas-pasan atau staf NGO yang kerjanya keliling ke daerah-daerah terpencil. Bukan bermaksud meremehkan, tapi bayangan saya waktu itu adalah kerja kantoran, pakai kemeja rapi, duduk di ruangan ber-AC. Realita? Jauh dari itu. Saya malah sempat jadi freelancer yang nulis laporan penelitian buat orang lain, sambil bantu-bantu usaha kecil keluarga di kampung.
Di tengah kondisi yang nggak menjanjikan itu, sosiologi justru jadi semacam “kacamata” yang bikin saya nggak cuma ngeluh sama keadaan. Saya mulai ngeliat, ternyata nggak cuma saya yang berjuang. Misalnya, waktu saya ngobrol sama pedagang di pasar dekat rumah, saya sadar mereka juga menghadapi ketidakpastian ekonomi, tapi tetep survive dengan cara mereka sendiri. Dari situ, saya inget teori sosiologi tentang agency—kemampuan orang untuk bertindak dan bikin perubahan meski dalam situasi sulit. Saya mikir, “Kalau mereka bisa, kenapa saya nggak?”
Sosiologi ngajarin saya ngga cuman lihat dari satu perspektif saja. Misalnya kenapa sulit banget dapat kerja? Bukan karena saya “kurang beruntung” atau “kurang skill” tapi ada struktur sosial yang main di belakang layar. Pasar kerja yang cukup ketat, prioritas perusahaan yang lebih memilih tenaga berpengalaman hingga sistem pendidikan yang ngga selalu nyambung sama kebutuhan industry. Ini bukan aja masalah personal tetapi ada sistem yang terbentuk.
Buat yang ngerasa sosiologi itu cuma ilmu “ngalor-ngidul,” saya pengin bilang: coba deh lihat sekitar kamu pakai kacamata sosiologi. Kenapa temen kamu stress gara-gara media sosial? Kenapa tetangga ribut soal politik? Atau kenapa kamu sendiri ngerasa stuck di hidup yang sekarang? Sosiologi bantu kamu nyambungin titik-titik itu. Nggak harus jadi akademisi atau peneliti. Bahkan di pekerjaan yang nggak related sama sosiologi, kemampuan memahami dinamika sosial ini bikin kamu lebih peka, lebih bisa nyelesaiin masalah, dan yang pasti, lebih manusiawi.
Sekarang, meski saya masih belum punya pekerjaan “impian” kayak yang dulu saya bayangin, saya nggak lagi ngerasa sosiologi itu sia-sia. Justru karena ilmu ini, saya bisa ngeliat peluang di tempat yang nggak terduga, kayak bikin workshop kecil buat anak-anak muda di kampung tentang literasi media, atau bantu temen bikin campaign sosial. Sosiologi nggak cuma bikin saya ngerti masyarakat, tapi juga bikin saya percaya bahwa di tengah ketidakpastian, kita selalu punya cara untuk bikin hidup lebih bermakna—buat diri sendiri dan orang lain.
Membumikan Sosiologi
“Bagaimana membumikan sosiologi?” Itu kayak nanya: gimana caranya bikin sosiologi nggak cuma jadi bahan diskusi di kelas, tapi bisa nyentuh hidup sehari-hari?
Nah, gini jawabannya, gaya santai tapi nendang, aku akan jelasin pakai bahasa bayi!
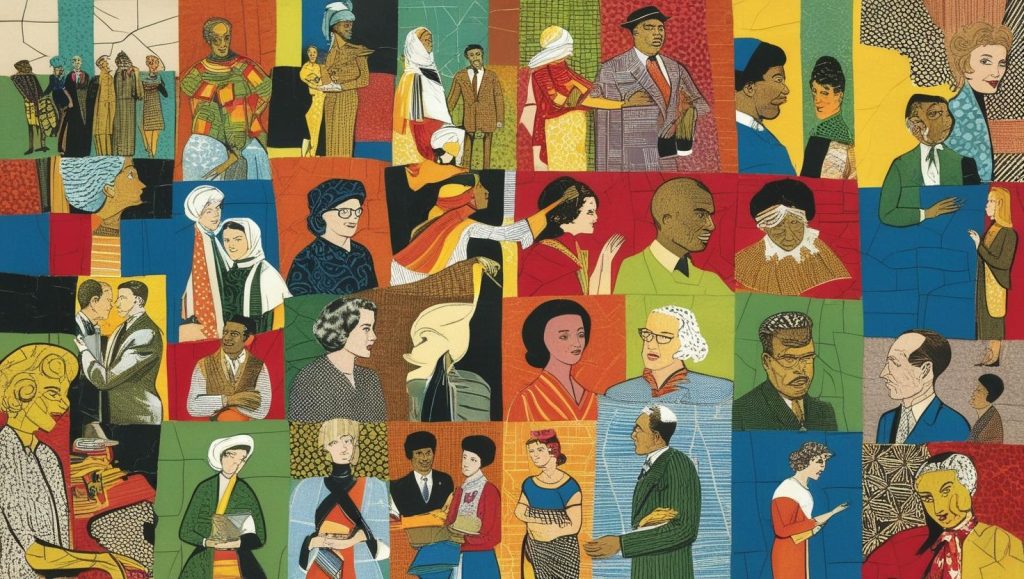
1. Bikin Sosiologi Dekat Sama Hidup Nyata
Sosiologi tuh bukan cuma tentang teori atau tokoh, tapi tentang ngerti kenapa hal-hal di sekitar kita itu terjadi. Kenapa perempuan lebih banyak jadi korban kekerasan? Kenapa pengamen dilarang tapi konser mahal dipuja? Itu semua bisa dikupas pakai kacamata sosiologi.
2. Gunakan Bahasa Manusia, Bukan Bahasa Dewa
Membumikan sosiologi berarti berani nurunin bahasa teori ke bahasa sehari-hari. Misalnya: Alih-alih bilang “relasi kuasa dalam institusi patriarki”, lo bisa bilang “kenapa suara perempuan sering dikesampingkan dalam rapat keluarga?”. Simpel, tapi mengandung teori.
3. Sosiologi di TikTok, Reels, dan Warung Kopi
Ngomongin sosiologi nggak harus di seminar. Bisa lewat video pendek, thread Twitter, atau ngobrol di tongkrongan. Kadang, penjelasan tentang “kenapa kelas sosial itu ngaruh ke gaya hidup” lebih nyampe lewat contoh lucu kayak: “Orang kaya ngopi di Starbucks, orang biasa ngopi di warkop. Bedanya cuma tempat, tapi maknanya kelas sosial.”
4. Ceritain, Bukan Ceramahin
Orang lebih gampang nyambung sama cerita. Jadi, sosiologi bisa dibumikan lewat kisah, baik itu pengalaman pribadi, kisah tetangga, atau cerita fiksi yang relate. Cerita bikin teori jadi hidup.
5. Jadi Peka, Bukan Sok Tahu
Membumikan sosiologi itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal mendengar. Dengerin curhat orang, keluhan warga, suara anak jalanan di mana semua itu bahan mentah sosiologi. Bukan buat dihakimi, tapi buat dipahami.
Intinya, sosiologi itu kayak kacamata:
Kalau kamu pakai dengan benar, kamu bisa lihat dunia lebih jernih termasuk ketidakadilan dan potensi perubahan.