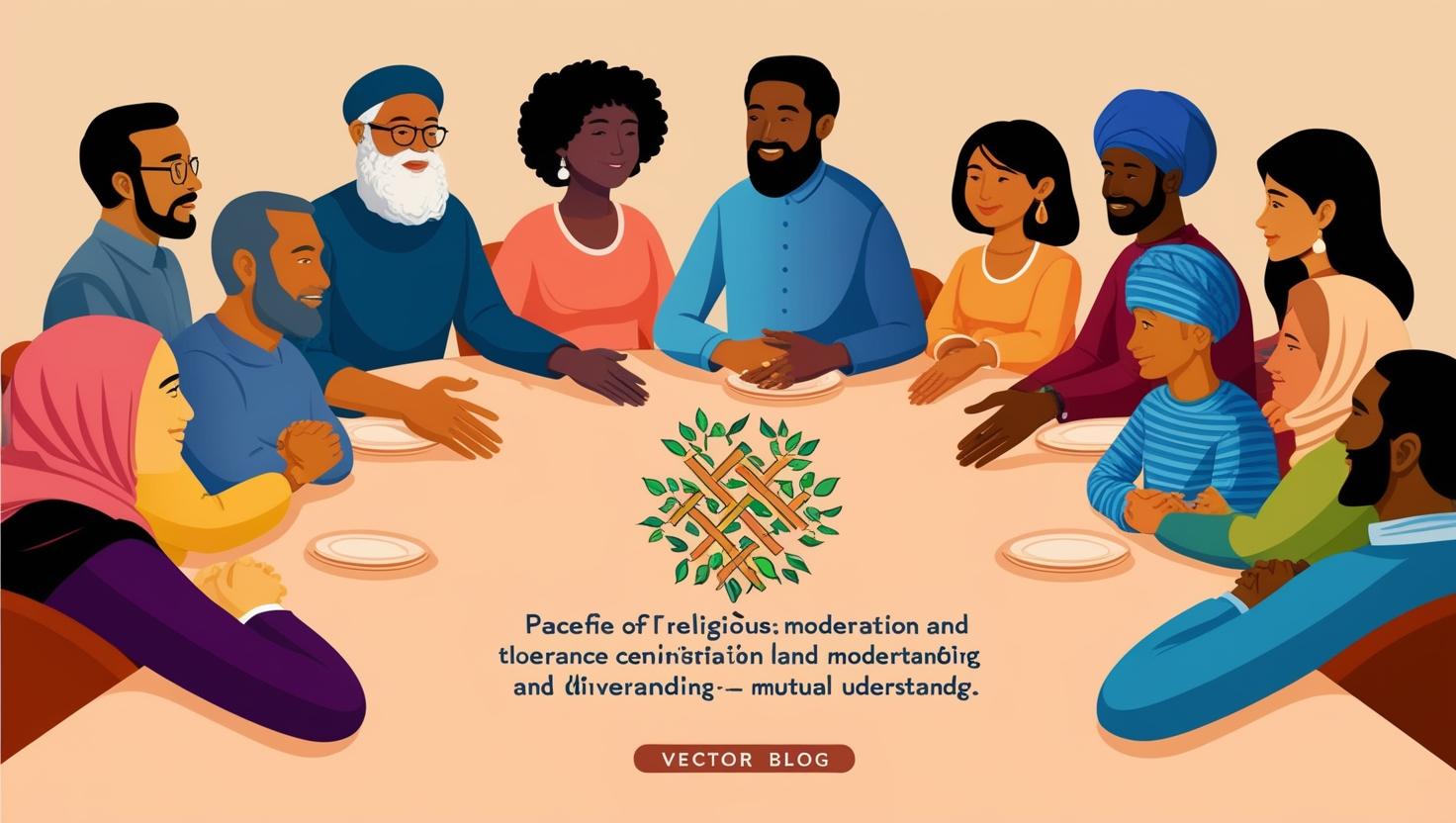Hari ini, banyak dari kita hidup dalam dua dunia. Yang pertama: dunia nyata, yang sering kita sembunyikan. Yang kedua: dunia digital, yang kita poles seindah mungkin. Di media sosial, kita tersenyum lebar, menampilkan rutinitas yang “produktif”, outfit yang estetik, dan kutipan motivasi yang bijak padahal hati sering kosong, cemas, atau bahkan merasa kehilangan arah. Kita terbiasa memakai topeng, bukan hanya di depan orang lain, tapi juga di hadapan diri sendiri. Di tengah dunia seperti ini, Imam Al-Ghazali datang seakan membisikkan sesuatu yang sangat dalam: “Lepaskan semuanya. Kembali ke Yang Satu. Itulah tauhid.”
Tauhid menurut Al-Ghazali bukan cuma soal mengakui bahwa Allah itu Esa. Itu baru lapisan paling luar. Tauhid yang sejati adalah ketika hati kita *tak lagi melihat selain Allah. Bukan sekadar lisan yang berkata “La ilaha illallah”, tapi seluruh kesadaran kita luruh dari segala ilusi, topeng, dan pencitraan. Kita lepas dari rasa ingin dipuji, lepas dari pencarian validasi, dan mulai hidup dalam keikhlasan. Inilah yang disebut Al-Ghazali sebagai fana* lenyapnya kesadaran terhadap ego dan dunia, lalu yang tersisa hanya Allah.
Di zaman sekarang, konsep *fana* ini terasa begitu kontras. Dunia kita justru dipenuhi *fake life*: kehidupan palsu yang dibangun dari citra, bukan dari kenyataan. Kita lebih takut kehilangan followers daripada kehilangan arah hidup. Kita lebih rajin edit foto daripada memperbaiki hati. Kita terus mencari eksistensi, padahal yang kita butuhkan adalah *inti dari eksistensi itu sendiri: Allah*.
Al-Ghazali mengajarkan bahwa *selama hati kita masih terikat pada pujian, status sosial, atau pencapaian semu, tauhid kita belum sempurna.* Bahkan itu bisa jadi bentuk syirik tersembunyi. Bukan karena kita menyembah berhala, tapi karena kita menggantungkan hati pada sesuatu selain Allah. Kita menjadikan pengakuan manusia sebagai “tuhan kecil” yang menentukan nilai diri kita.
Namun jangan salah, tauhid bukan berarti menyendiri dan memutuskan hubungan dari dunia. Tauhid adalah tentang *hidup di dunia, tapi tidak diperbudak olehnya.* Menyentuh realitas, tapi tak terjebak dalam palsunya. Muncul di media sosial, tapi tidak tenggelam dalam pencitraan. Sebab orang yang bertauhid sejati, justru akan tampil lebih jujur, lebih utuh, dan lebih damai.
Jadi, di tengah dunia yang penuh topeng ini, mungkin saatnya kita bertanya: *apa yang sedang kita kejar? Untuk siapa kita hidup? Siapa yang benar-benar kita kenal Allah, atau hanya versi palsu dari diri sendiri?*
Fana bukan tentang menghilang dari dunia, tapi tentang melepaskan yang palsu agar bisa benar-benar hadir. Dan tauhid, dalam makna terdalamnya, bukan hanya teologi ia adalah seni hidup yang paling jujur: *hidup hanya untuk dan karena-Nya.*
Wallahua’lam biishowab